Sejarah Syekh Siti Jenar selalu berlapis kabut. Namanya disebut dengan takzim sekaligus curiga, disanjung dalam satu bait tembang, lalu dikutuk dalam catatan kerajaan. Ia tokoh yang hidup di antara legenda dan penghapusan. Begitu besar pengaruhnya hingga para penguasa merasa perlu menghapus jejaknya, menuduhnya sesat, bahkan menciptakan mitos-mitos yang membuat rakyat menjauh dari ajarannya.
Dalam banyak naskah, Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai ulama sekaligus “pemberontak spiritual” abad ke-15. Ia lahir di Caruban (kini Cirebon) dari keluarga ulama asal Malaka, dan sejak kecil sudah menempuh pendidikan agama di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Tapi jalan hidupnya berbeda: ia tidak berhenti pada teks, ia mencari makna. Setelah menempuh pengembaraan rohani ke Pajajaran, Palembang, dan Baghdad, ia kembali ke Jawa membawa gagasan baru tentang hakikat manusia.
Ajarannya mengguncang. Di saat Islam baru tumbuh di tanah Jawa sebagai sistem kerajaan dan syariat formal, Siti Jenar berbicara tentang penyatuan manusia dengan Tuhan, tentang hakikat diri, tentang kemerdekaan batin. Ia tidak melawan Islam—ia melawan cara berpikir sempit yang menjadikan agama sebagai alat kuasa.
Maka lahirlah upaya besar untuk “mengubur” namanya. Naskah-naskah resmi abad ke-16 dan 17 menulis kisah yang saling bertentangan: sebagian menyebutnya ulama sufi, sebagian menuduhnya sesat, bahkan ada yang menulis ia lahir dari cacing. Pengaburan sejarah itu bukan tanpa maksud. Dengan mengaburkan asal-usulnya, ajarannya ikut dikaburkan.
Lima Mitos dan Pelurusan Jejak Sejarah Syekh Siti Jenar
Sejarah Syekh Siti Jenar bukan dongeng, tapi banyak yang berusaha menjadikannya mitos agar aman untuk dilupakan. Padahal, menelusuri jejaknya bukan hanya soal mencari siapa dia, tapi juga mencari kebenaran tentang bagaimana Islam tumbuh di tanah yang penuh keragaman.
Pertama, mitos bahwa Siti Jenar lahir dari cacing. Cerita ini adalah bentuk penghinaan politik, bukan fakta. Dalam naskah Serat Candhakipun Riwayat Jati, tertulis bantahan tegas:
“Wondene kacariyos yen Lemahbang punika asal saking cacing, punika ded, sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon.”
Artinya: Siti Jenar memang manusia biasa, rakyat kecil dari desa Lemah Abang.
Kedua, mitos bahwa ia mengajarkan “manunggaling kawula gusti” dalam arti menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal, istilah itu tak pernah muncul dalam ajarannya. Ia menggunakan konsep fana’ wal baqa’ — ajaran tauhid tentang lenyapnya ego manusia di hadapan keabadian Allah. Ia bukan penganut paham sesat, justru penganut tauhid sejati.
Ketiga, tuduhan bahwa ia meninggalkan salat, puasa, dan syariat Islam. Banyak naskah kuno dan kesaksian muridnya, seperti Syaikh Burhanpuri, justru menulis bahwa Siti Jenar dikenal tekun beribadah, berpuasa Daud, dan tak pernah putus dzikir. Ia mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti di gerak, tapi harus sampai pada makna.
Keempat, cerita bahwa Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo. Tak ada bukti sejarah yang meyakinkan soal itu. Kisah ini muncul berabad-abad kemudian, ditulis dalam naskah sastra untuk menonjolkan citra Dewan Wali sebagai otoritas agama. Dalam konteks politik Islam awal di Jawa, cerita ini lebih mirip simbol benturan antara spiritualitas dan kekuasaan.
Kelima, fitnah bahwa jenazahnya berubah menjadi anjing. Inilah bentuk penghinaan paling kasar terhadap seorang waliyullah. Riwayat para ulama justru menyebut beliau wafat dalam keadaan sujud setelah salat tahajud di Masjid Agung Cirebon. Dalam tradisi Jawa, ungkapan simbolik seperti itu sering dipakai untuk menggambarkan “penghilangan jejak” — bukan perubahan fisik.
Dari lima mitos itu, tampak jelas: sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang mencari kebenaran, tapi oleh mereka yang ingin menenangkan kekuasaan. Mengingat Syekh Siti Jenar berarti mengingat bahwa kebenaran bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dimusnahkan.
Menyusun Ulang Cermin yang Retak
Mempelajari sejarah Syekh Siti Jenar bukan sekadar membaca masa lalu, tapi menata ulang cermin yang telah dipecahkan oleh waktu. Potongan-potongan kisahnya tercecer di naskah, di tradisi lisan, di tembang dan suluk Jawa. Dari setiap keping itu, kita melihat seorang manusia yang berani menempuh jalan berbeda, bukan demi melawan, tapi demi memahami.
Ia bukan nabi, bukan malaikat, tapi manusia yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhannya. Ia belajar dari kitab sufi besar—Ibnu Arabi, Al-Jili, Al-Hallaj, Al-Ghazali—dan menjadikannya bahasa lokal dalam budaya Jawa. Ajarannya tentang ilmu kasampurnan adalah upaya menyatukan spiritualitas Arab dengan kebijaksanaan Nusantara. Di titik itu, ia adalah jembatan antara langit dan tanah Jawa.
Kini, ketika agama sering kembali dijadikan alat politik dan tafsir disempitkan oleh kepentingan, kisah Siti Jenar terasa semakin relevan. Ia mengingatkan kita bahwa Islam tidak pernah datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan. Dan bahwa kadang, yang disebut sesat hanyalah mereka yang berjalan lebih jauh dari keberanian zamannya.
Sejarah Syekh Siti Jenar bukan sekadar kisah masa lalu, tapi cermin tentang siapa kita hari ini—masyarakat yang kadang lebih mudah percaya pada fitnah daripada memahami makna.
Kalau kamu punya tafsir lain tentang kenapa nama-nama seperti ini disembunyikan, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, dengan saling berbagi cerita, kita bisa memungut kembali serpihan kebenaran yang pernah dipecahkan sejarah.
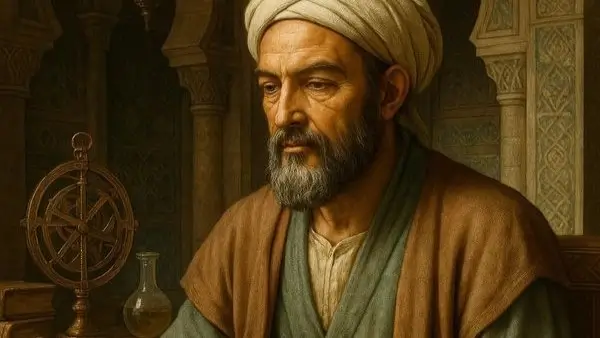
Artikel yang sangat inspiratif dan penting! Sungguh menguatkan hati melihat organisasi ini tak hanya menyoroti urgensi krisis iklim, tetapi juga memberikan solusi konkret dan harapan melalui aksi kolektif. Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim dan semua pihak yang terlibat dalam upaya membangun kesadaran serta mendorong perubahan nyata. Tulisan seperti ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah kecil—dari individu hingga kebijakan global—berkontribusi besar bagi masa depan bumi. Terima kasih telah menjadi suara yang konsisten dan progresif dalam perjuangan ini. Mari terus bergerak bersama; semangat dan dedikasi kalian adalah sumber motivasi bagi banyak orang!”
Intesting content, will share with friends