Saya sering berpikir, kapan tepatnya kita mulai menilai moral seseorang dari kain yang menutup kepalanya? Pertanyaan ini muncul setiap kali saya mendengar orang memuji perempuan berjilbab sebagai “salehah,” seolah jilbab, kesalehan, dan persepsi moral selalu berjalan seiring. Padahal, antara simbol, makna, dan perilaku sering kali terbentang jarak yang tak kasatmata.
Jilbab memang lahir dari ruang religius, tapi ketika ia dijadikan ukuran kesalehan, kita mulai menilai manusia bukan dari hatinya, melainkan dari kulit luarnya.
Antara Citra dan Nurani
Di dunia yang serba visual, citra mudah mengalahkan nurani. Foto, video, dan unggahan media sosial menampilkan kesalehan dalam bentuk yang kasat mata—pakaian, gaya, atau label religius. Namun kesalehan sejati jarang berisik. Ia tumbuh diam-diam di ruang yang tidak tersentuh kamera: di hati, dalam niat, dan pada cara kita memperlakukan sesama.
Ketika jilbab dipakai demi pengakuan sosial, makna spiritualnya perlahan memudar. Pakaian yang semestinya menjadi ruang kesadaran berubah menjadi panggung moral. Kita tak lagi bertanya mengapa seseorang berhijab, melainkan apa pesan yang ingin ditunjukkannya kepada dunia.
Namun saya tidak sedang menghakimi. Karena manusia, termasuk kita, sering kali butuh simbol untuk berpegang pada nilai-nilai yang diyakini. Kita butuh sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh sebagai tanda keimanan. Hanya saja, simbol kehilangan makna jika tidak dihidupi oleh kesadaran batin.
Saat Jilbab Menjadi Ukuran Moral
Di beberapa tempat, perempuan masih dinilai dari caranya berpakaian: terlalu ketat dianggap dosa, terlalu longgar dianggap kolot. Di sini jilbab, kesalehan, dan persepsi moral kerap bertabrakan. Moral berubah menjadi pakaian, bukan perilaku. Agama menjadi pengawasan sosial, bukan refleksi pribadi.
Padahal sejarah Islam tidak mengenal keseragaman bentuk busana. Nabi tidak pernah menetapkan satu model tertentu. Para ulama pun berbeda pendapat soal batas aurat dan cara berpakaian. Ini menunjukkan bahwa berpakaian dalam Islam punya ruang tafsir yang luas, selama esensi kesopanan dan penghormatan tetap dijaga.
Perempuan Muslim yang memakai kebaya, jeans, atau selendang sederhana bisa sama salehnya dengan yang memakai abaya hitam dari Arab. Karena ukuran iman tidak diukur dari panjang kain, tapi dari panjang kesabaran dan keluasan hati.
Seperti kata Prof. Sumanto Al Qurtuby, “Hidayah itu urusan hati, bukan sehelai kain.”
Kutipan itu sederhana tapi dalam. Ia menegaskan bahwa kesalehan sejati tidak bisa dijahit dari bahan busana, melainkan dijaga dari niat yang tulus.
Menemukan Kembali Arti Kesalehan
Kita hidup di zaman di mana agama sering dijadikan identitas, bukan perjalanan spiritual. Maka, mungkin sudah saatnya kita bertanya: bagaimana agar jilbab, kesalehan, dan persepsi moral tidak berhenti di simbol? Bagaimana agar busana tidak menjadi alat penghakiman, melainkan ruang perenungan?
Saya percaya, kesalehan sejati tidak membutuhkan panggung. Ia hadir dalam diam, melembutkan hati, dan menumbuhkan empati. Jilbab yang dikenakan dengan kesadaran seperti itu akan memantulkan cahaya yang tenang—bukan dari kainnya, tapi dari jiwa yang memakainya.
Pada akhirnya, jilbab, kesalehan, dan persepsi moral adalah kisah manusia tentang pencarian makna. Tentang bagaimana kita belajar melihat Tuhan bukan di kepala orang lain, tapi di dalam diri sendiri.







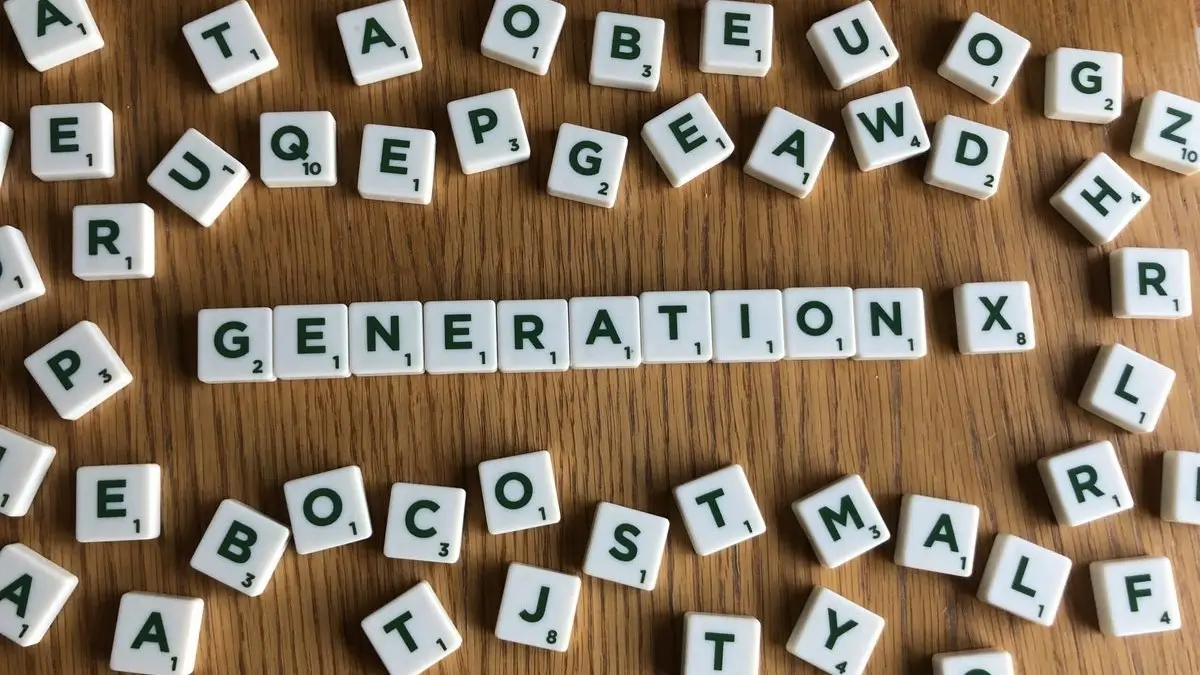




Leave a Review